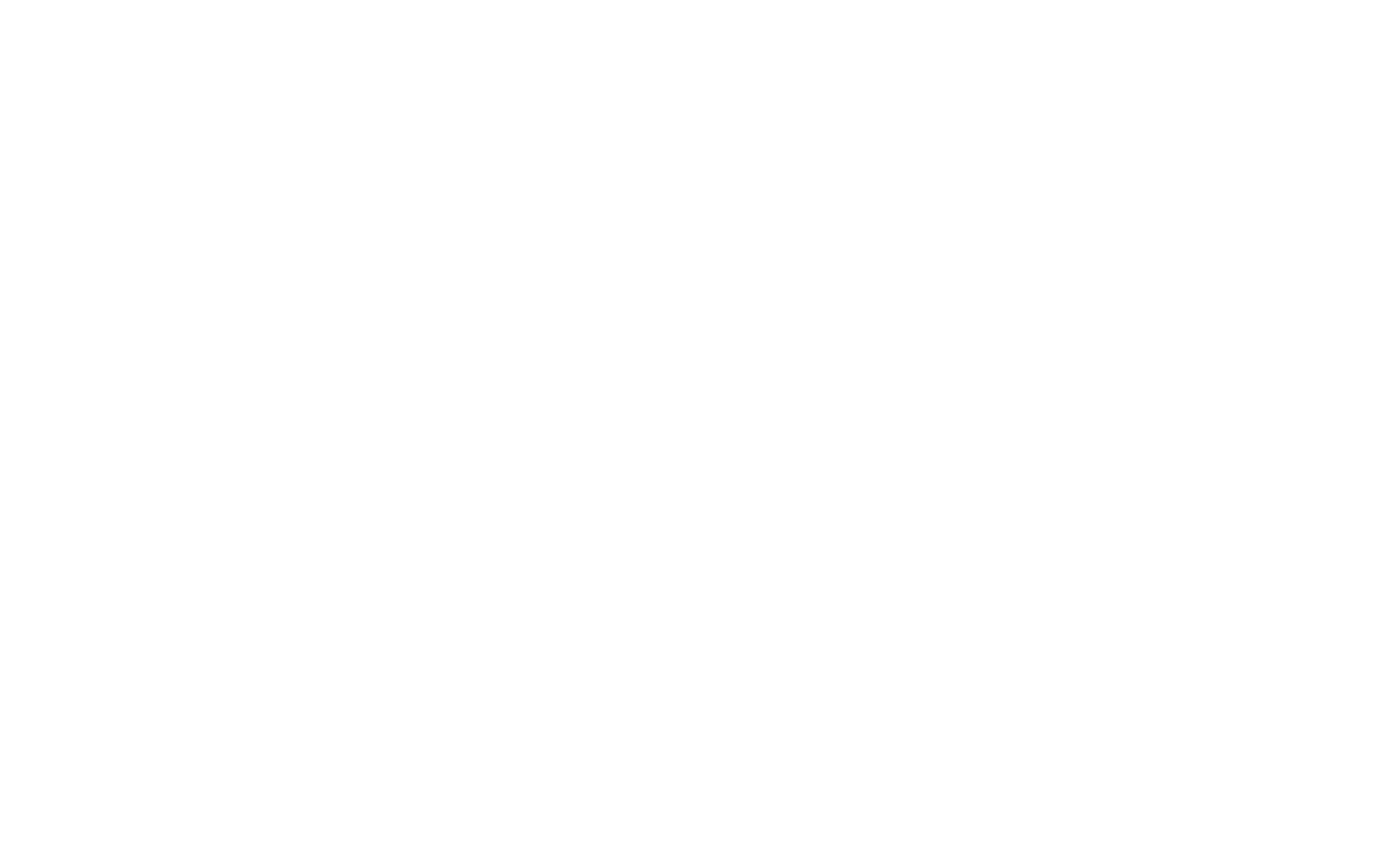“When ‘I’ replaced with ‘We’, even the illness becomes wellness.” – Malcolm X
Pada 2 Maret 2020, Presiden Joko Widodo, bersama dengan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, mengumumkan adanya dua orang warga Indonesia yang tercatat positif mengidap Virus corona, diduga karena salah satunya melakukan kontak dansa dengan warga negara Jepang. Pengumuman ini sekaligus juga menandakan bahwa virus Corona (yang disinyalir berawal dari Wuhan, Tiongkok, dan telah menyebar ke banyak negara) sudah resmi berjangkit di Indonesia. Namun di hari yang sama, presiden mengumumkan pemberian insentif sebesar 1 Triliun Rupiah bagi beberapa maskapai penerbangan dalam bentuk diskon tiket pesawat, tak lain dikarenakan adanya penurunan jumlah wisatawan asing yang datang ke Indonesia. Sementara di hari itu juga, tercatat sebanyak 89.212 orang telah terinfeksi virus corona di seluruh dunia dan sebanyak 3.048 jiwa dinyatakan tewas karenanya.
Lantai Dansa itu Bernama Pandemi
Sejak awal kemunculan virus corona (yang kemudian disebut sebagai Covid 19), media di Indonesia disesaki pernyataan-pernyataan kontroversial, bahkan sikap menyepelekan dari pejabat pemerintah. Tidak hanya itu, kebijakan-kebijakan yang mereka ambilpun jauh dari efektif. Ketimbang melakukan langkah-langkah pencegahan agar virus tak semakin meluas, berikut pembenahan sistem dan fasilitas kesehatan bagi mereka yang kadung terjangkit, ratusan miliar justru dikeluarkan dari dompet negara demi memberikan insentif bagi maskapai penerbangan agar dapat menurunkan harga tiketnya. Tidak hanya itu diskon 30% diberikan bagi wisatawan yang menghabiskan uangnya di Indonesia. Jasa para punggawa sosial media atau para influencer pun dikerahkan, demi menarik wisatawan domestik dan mancanegara. Semua itu dilakukan justru di tengah kepanikan penanganan Covid-19 dan langkah sigap oleh banyak negara dalam melakukan penutupan akses dan larangan penerbangan. Pandemi yang membawa derita bagi banyak orang, justru dijadikan ajang menarik pundi-pundi kapital bagi pemerinta Indonesia, dengan memanfaatkan ketakutan dan diberlakukannya penutupan akses berikut larangan terbang ke beberapa negara zona merah. Semua atas nama devisa, dan dalih kebal Corona. Satu-satunya ketakutan adalah runtuhnya ekonomi di tengah rapuhnya keamanan negara.
Masyarakat pun dibuat bingung, kita disuguhi beragam paradoks, antara senyum lebar Menteri Kesehatan kala mengumumkan masuknya virus Covid-19 di Indonesia dengan jumlah korban tewas yang terus meroket. Antara pemberlakuan diskon wisata dengan diberlakukannya larangan terbang bahkan penutupan akses di banyak negara. Antara gencarnya negara-negara lain melakukan lockdown dengan himbauan pemerintah Indonesia untuk jangan takut berlibur. Informasi yang kabur dan pernyataan yang jauh dari menyejukan dari para pejabat negara, membuat masyarakat berinisiatif mencari informasi sendiri. Rakyat yang pada awalnya turut terkekeh dan mengamini fakta sumir tentang ‘kekebalan’ kita akan virus, pada akhirnya dipaksa untuk membuka mata dan sadar bahwa bencana sudah di depan mata, sehingga bersikap abai apalagi sampai pergi berwisata sama sekali bukan jawaban.
Tidak butuh waktu lama untuk pemerintah tak lagi dapat berdalih. Pada akhirnya kenyataan berbanding terbalik dengan pernyataan-pernyataan sensasional para pejabat dan himbauan untuk tidak khawatir dengan Covid-19. Empon-empon, doa qunut, apa lagi susu kuda liar, terbukti tak cukup sakti untuk mencegah Covid-19 nenancapkan taringnya semakin dalam di Indonesia. 11 Maret 2020, untuk pertama kalinya, seorang warga negara Indonesia dinyatakan meninggal karena mengidap Covid-19.
Langkah yang Telat di Malam yang Makin Pekat
Pengumuman kasus pertama Covid-19, tidak dibarengi dengan penyebaran pengetahuan akan mitigasi. Rakyat tidak mendapat informasi yang cukup mengenai langkah-langkah mitigasi mandiri pencegahan virus corona. Malam hari setelah pengumuman, terjadi panic buying di kota-kota besar yang menyebabkan kelangkaan sembako, masker, dan hand sanitizer. Untuk masalah yang pertama disebutkan memang tidak terjadi di Jogjakarta, namun kelangkaan masker dan hand sanitizer hampir terjadi di setiap kota tidak terkecuali Jogjakarta.
Semakin berkembangnya kasus penularan dan korban jiwa, memaksa pemerintah untuk mulai melakukan langkah-langkah pencegahan dan penanganan Pandemi. Hal yang seharusnya dilakukan jauh-jauh hari, apalagi mengingat bahwa pada tanggal 9 Februari Tim peneliti dari Harvard T.H. Chan School of Public Health di Amerika Serikat, menyatakan bahwa virus corona sebenarnya telah masuk ke Indonesia. Bukannya dilihat sebagai alarm peringatan untuk mulai melakukan penanganan, pernyataan ini justru ditanggapi oleh pemerintah dengan berapi-api sebagai tudingan murahan. Dengan tertatih-tatih pemerintah mulai membuat sistem pencegahan dan pengobatan untuk pandemi, langkah nyata yang tentu saja terlambat.
Dikutip dari Reuters, sistem penanganan kesehatan Indonesia sangat buruk bila dibandingkan dengan negara-negara lain yang terdampak COVID-19. Negara berpenduduk lebih dari 260 juta orang ini hanya memiliki 321.544 tempat tidur rumah sakit. Artinya, hanya tersedia sekitar 12 tempat tidur bagi 10.000 orang. Sementara sebagai perbandingan, menurut WHO, Korea Selatan memiliki 115 tempat tidur rumah sakit bagi 10.000 orang. Masih menurut WHO, pada 2017 diketahui bahwa Indonesia memiliki empat dokter per 10.000 orang. Dari hasil studi dalam jurnal Critical Care Medicine yang terbit pada Januari 2020, disebutkan bahwa perbandingan tempat perawatan intensif bagi pasien dewasa di Indonesia adalah 2,7 ruang ICU per 100.000 orang. Termasuk yang terendah bagi negara-negara Asia berdasarkan data 2017.
Di tengah keterbatasan fasilitas kesehatan tersebut, pasien corona masih harus berbagi dengan pasien lain seperti demam berdarah yang jumlahnya tidak sedikit. Belakangan, pasien Covid19 membludak melebihi kapasitas yang mengakibatkan tenaga medis kesulitan untuk melakukan perawatan. Bahkan, gedung Wisma Atlit di Jakarta yang dialihfungsikan untuk pasien Covid19 pun tidak mampu menampung banyaknya pasien yang terdiagnosis Covid-19.
Jika rakyat kebanyakan sulit mengakses masker dan hand sanitizer, maka tenaga medis kesulitan mengakses Alat Pelindung Diri (APD) untuk merawat pasien terjangkit virus corona yang juga biasa disebut baju hazmat. Kurangnya fasilitas kesehatan membuat para tenaga kesehatan harus berkompromi dengan keselamatan kerjanya. Baju hazmat berikut pelengkap APD yang idealnya hanya digunakan sekali pakai, terpaksa mereka gunakan selama tiga hari. Para nakes di Banten bahkan harus mensteril APDnya sendiri di rumah. Hal ini tentu juga membawa resiko terinveksinya penyakit bagi keluarga mereka di rumah. Sebuah video viral dari Tasikmalaya menunjukkan fakta yang ironis, dimana para nakes terpaksa mengevakuasi pasien terjangkit Covid19 dengan menggunakan jas hujan plastik yang biasa digunakan oleh pengendara motor. Ternyata ini tidak hanya terjadi di Tasikmalaya, melainkan juga di Sukabumi, Lombok Timur, Kabupaten Manggarai, Tana Toraja, Aceh, Samarinda.
Permasalahan penanganan Covid-19 dari segi kesehatan, tidak hanya dari fasilitasnya saja, melainkan juga tenaga kesehatannya sendiri. Tercatat hingga November 2020, terdapat 282 orang tenaga kesehatan gugur selama masa pandemi. Tidak idealnya APD yang mereka kenakan, berikut masa tugas mereka yang kelewat panjang hingga tubuh mereka tidak lagi fit, menyebabkan resiko nakes terinfeksi virus teramat besar.
Harta, Tahta dan WFH
31 Maret 2020, pemerintah Indonesia berkeputusan untuk menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) dan Keputusan Presiden (Keppres) terkait status kedaruratan kesehatan masyarakat. Selama PSBB berlangsung, pemerintah menghimbau warga untuk melakukan karantina mandiri dan melarang melakukan aktivitas di luar rumah, dan melakukan pengawalan dengan menurunkan Satpol PP, Polisi, hingga TNI, untuk “menertibkan” dan membubarkan setiap kerumunan. Selain itu, aktivitas perkantoran dan kegiatan belajar-mengajar di institusi pendidikan dipindahkan menjadi kegiatan daring yang dikenal dengan Work From Home (WFH). Warga dihimbau untuk tidak keluar rumah, kecuali untuk kegiatan belanja bahan makanan.
Penerapan karantina mandiri dan bekerja dari rumah tentu efektif dalam menekan laju penyebaran virus, namun dengan catatan seluruh kebutuhan dasar warga terpenuhi selama masa karantina. Beberapa orang mungkin tidak masalah bekerja dari rumah atau menangguhkan pekerjaan mereka, karena masih digaji atau masih memiliki simpanan yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya berikut keluarga selama karantina. Sementara lebih banyak orang lagi yang untuk memenuhi kebutuhan dasarnya untuk esok hari saja, ia harus bekerja keras hari ini.
Pada akhirnya penerapan stay at home dan work from home merupakan sebuah privilese. Tidak semua orang memiliki kemampuan untuk bisa melakukan karantina mandiri. Sebagian besar dari mereka tidak punya cukup dana untuk hanya sekedar makan dan berdiam diri di rumah. Kondisinya mereka harus memiliki dana untuk mencukupi sekedar kebutuhan dasar mereka, namun situasinya tidak memungkinkan mereka untuk mendapat dana yang cukup, sementara mereka tidak mendapat sokongan kebutuhan yang cukup dari pemerintah.
Selama periode awal penerapan PSBB, pemerintah memang memberi sokongan dana dan sembako bagi warga. Pembagian sembako yang uang tunai dilakukan, hanya bagi warga dan pekerja formal yang terdaftar, itupun dengan jumlah dan waktu yang terbatas, dan hanya di beberapa daerah saja (diutamakan daerah Jabodetabek dan sekitarnya). Kebijakan bekerja di rumah membuat banyak pabrik dan perusahaan terpaksa menutup tempat kerjanya, ribuan pekerja harus dirumahkan, dan tidak sedikit dari mereka yang akhirnya menghadapi pemutusan hubungan kerja (PHK). Pawa awal Agustus 2020, tercatat, sebanyak 3,5 juta kasus PHK terjadi di Indonesia, meninggalkan jutaan pengangguran dan kepala keluarga yang kesulitan menafkahi keluarga dan dirinya sendiri, hanya untuk bertahan hidup selama masa pandemi.
Lalu bagaimana nasib banyak pekerja informal dan penduduk yang tidak tercatat? Sayangnya tidak ada bantuan yang menyentuh mereka. Sebagian besar dari mereka tidak mungkin memindahkan aktivitasnya menjadi daring. Pemulung, kuli bangunan, tukang becak, ojek, buruh angkutan umum, buruh gendong, buruh pariwisata, pedagang pasar, dan sejenisnya, mau tidak mau tetap harus bekerja di luar rumah, tentu dengan resiko kesehatan yang lebih besar. Di pasar tradisional, pedagang masih berjualan meski lebih banyak yang memilih tutup, dan di jalan-jalan, tukang becak masih banyak yang terlihat mangkal menunggu orang yang memakai jasanya, kendati sedikit atau tidak ada yang membeli jasa dan barang dagangannya.
Sepinya pembeli dipengaruhi oleh PSBB dan lockdown mandiri yang dilakukan hampir di seluruh perkampungan di Jogjakarta. Bahkan pemulung di perkotaan, kesulitan melanjutkan pekerjaannya karena akses masuk ke perkampungan ditutup dan dijaga oleh warga setempat. Hal tersebut juga berlaku bagi buruh wisata dan pelaku usaha lain yang bergantung pada situasi “normal” sebelum pandemi berlangsung, di mana orang-orang bebas beraktivitas di luar rumah untuk bekerja, sekolah/kuliah, belanja, sekadar nongkrong, dan liburan, tanpa rasa takut untuk tertular virus ketika berinteraksi dengan orang lain. Terhambatnya aktivitas ekonomi, berpengaruh besar pada penghasilan, bahkan untuk sekadar memenuhi kebutuhan dasar harian. Beberapa terpaksa melanjutkan hidup dengan utang, sampai keadaan “normal” yang ia sendiri tidak tahu kapan itu terjadi.
Pada akhir Maret 2020, beredar video di media sosial, seorang dokter dan perwira polisi mendatangi rumah keluarga seorang pengusaha. Di rumah tersebut, seluruh keluarga dan karyawan kantor pengusaha yang berjumlah 80 orang tadi dites darah dan rontgen untuk mengetahui apakah ada yang terjangkit virus corona atau tidak. Belakangan diketahui bahwa, setelah mendapat banyak kecaman, nama pengusaha tersebut adalah Jerry Hermawan Lo, seorang pengusaha properti, dan mobil kesehatan sekaligus dokternya berasal dari RS Royal Progress. Kemudian polisi yang terlihat dalam video ialah Ketum PSSI Komjen Pol. Mochammad Iriawan, atau yang dikenal dengan Iwan Bule.
Video tersebut mendapat respon beragam dari warganet, tidak sedikit yang mengkritik bahkan mengecam tindakan si pengusaha karena dengan statusnya sebagai orang kaya dianggap memiliki keistimewaan dari pemerintah.
Kecaman dari warganet disebabkan oleh minimnya tes yang dilakukan oleh pemerintah terhadap warga dan mahal jika dilakukan tes secara mandiri, yang artinya hanya bisa dilakukan oleh orang-orang kaya. Sampai 18 Juni, hanya 2.126 orang yang dites Covid-19 per 1 juta penduduk di Indonesia. Capaian Indonesia masih di bawah Malaysia yang sanggup melakukan 20.536 tes per 1 juta penduduk, Vietnam dengan 2.826 per 1 juta penduduk, atau Korea Selatan dengan 22.348 tes per 1 juta penduduk.
Ketimpangan ekonomi begitu dirasakan oleh warga selama pandemi berlangsung. Bukan hanya masalah biaya tes yang mahal dan sulit diakses oleh mayoritas warga, namun juga dapat dirasakan dan dilihat dari bagaimana orang-orang kelas atas dan menengah ke bawah menjalani hidup selama PSBB. Warga kelas atas membangun kratifitas selama PSBB untuk membunuh rasa bosan dengan berbagai cara. Ada yang membuat kolam renang, membeli Playstation edisi terbaru sambal sesekali goyang untuk konten video Tik Tok. Sedang orang-orang dengan kelas rentan (menengah ke bawah) harus mencari banyak cara agar tetap bisa makan, bahkan jika risikonya harus tertular Covid19. Memang benar kalau Covid19 bisa menulari siapa saja tanpa mengenal kelas sosial, namun tetap saja, dampaknya begitu berbeda tergantung kelas sosialnya masing-masing.
Kala Saya Menjelma Kita: Gelombang gotong Royong selama Pandemi.
Pada masa awal pandemi perlahan menyusup ke kehidupan kita, beberapa toko dan apotek telah melaporkan semakin menipisnya persediaan masker dan hand sanitizer. Tidak butuh waktu lama sampai akhirnya kedua barang tersebut menjadi barang langka dan mendadak mahal dengan harga yang tidak masuk akal. Dalam satu wawancara, salah seorang pesohor menceritakan bagaimana ia terpaksa membeli sekotak masker dengan harga 2 juta rupiah secara daring, karena tidak lagi tersedia di toko atau apotek yang ia datangi. Sekotak masker yang biasanya hanya dijual tidak lebih dari 100 ribu rupiah di tiap apotek. Hal yang kurang lebih sama juga terjadi pada hand sanitizer dan sembako, khususnya beras. Harga yang meroket tak keruan dan kelangkaannya di toko-toko. Salah satu penyebabnya adalah ulah para penimbun. Mereka lebih dulu membeli barang-barang tersebut dalam jumlah banyak, untuk kemudian menjualnya lagi dengan harga menjulang.
Pada kondisi seperti itu, mudah untuk kita kehilangan harapan pada kemanusiaan. Saat sesama warga tidak lagi mau ambil pusing dengan penderitaan saudaranya, bahkan mengambil untung dari situ, siapa lagi yang bisa kita percaya dan gantungkan? Syukurlah hal tersebut tidak berlangsung lama. Pada kenyataannya, bencana membawa kita semakin dekat. Di tengah keputus asaan akan ancaman baru dan kekecewaan akan lambatnya penanganan pemerintah, rakyat pun bergerak mengambil alih kendali. Pada akhirnya kita sadar, kalau kita hanya bisa menggantungkan diri pada satu sama lain.
Pada masa awal pandemi, dimana tenaga kesehatan mengeluhkan kurangnya alat-alat pelindung kesehatan seperti masker, hand sanitizer dan baju hazmat, beberapa kelompok warga berjibaku di depan mesin jahitnya, menjadi ratusan masker kain, beberapa bahkan membuat baju hazmat dan hand sanitizer, tidak hanya bagi tenaga kesehatan, tapi juga bagi masyarakat luas. Beberapa pabrik tekstil beralih memproduksi masker yang dijual sangat murah. Sebuah pabrik minuman keras di Solo mengalihkan penggunaan ethanolnya untuk memproduksi hand sanitizer untuk dibagikan dan dijual murah.
Dari situ, solidaritas pun bergulir dengan bentuk yang semakin beragam dan efektif. Kurangnya informasi yang diberikan pemerintah, membuat banyak media daring, baik atas nama institusi maupun individu, bersama mencari dan menyebarluaskan informasi yang jauh lebih akurat bagi masyarakat, terutama terkait pencegahan berjangkitnya virus. Seorang pemilik penginapan di Semarang menyewakan kamar-kamarnya secara gratis, bagi tenaga kesehatan yang terusir dari tempat tinggalnya dikarenakan ketakutan akan stigma Covid. Beberapa kelompok pemuda memberikan jasa gratis dalam membeli dan mengantar bahan pangan, terutama bagi mereka yang lebih rentan terjangkit virus, seperti para orang lanjut usia. Bahkan para psikolog di beberapa kota menyediakan jasa konsultasi gratis bagi mereka yang mengalami depresi dan kecemasan mental dikarenakan pandemi, dan itu semua belum sepersepuluh dari gelombang saling jagaj saling bantu antar rakyat yang muncul karena pandemi.
Diantara seluruh hal yang dibutuhkan warga adalah pangan. Turun bahkan hilangnya penghasilan yang disebabkan oleh pandemi, menyebabkan banyak orang bahkan tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan makannya setiap hari. Karena kesadaran ini, maka salah satu solidaritas yang paling banyak muncul melibatkan pangan. Mulai dari berbagi sembako, hingga makanan jadi dilakukan oleh banyak elemen. Peruntukannya juga beragam, mulai dari tenaga kesehatan, pekerja informal, para lanjut usia, hingga paket pangan sehat bagi anak-anak.
Salah satu gerakan yang melibatkan paling banyak warga adalah Solidaritas Pangan Jogja (SPJ) di Yogyakarta. SPJ merupakan gerakan solidaritas saling berjejaring antar warga berupa dapur umum yang memasak makanan baik bagi komunitas dapurnya sendiri, juga untuk saling dibagikan ke warga lain yang membutuhkan. Seiring berjalan, SPJ telah berjejaring dengan 12 dapur di berbagai daerah tersebar di Yogyakarta. Tiap dapur yang tergabung dalam jaring solidaritas SPJ berlaku sebagai sel otonom, dimana tiap dapur dikelola secara mandiri oleh tiap komunitas warga di mana masing-masing dapur berada. Lewat dana donasi dari publik, tiap dapur mengelola pengeluaran bahkan pemasukannya sendiri,dengan melibatkan banyak pihak seperti pemulung, buruh perkotaan, petani, pekerja seks, hingga mahasiswa.
SPJ bisa dibilang salah satu gerakan solidaritas yang terbukti efektif. Ia hadir tidak dengan semangat beramal, namun semangat berbagi dan saling bantu. Seperti semangat gotong royong (mutual aid) antar warga, dimana setiap elemen yang terlibat sama pentingnya dengan yang lain. ‘Kami turun tangan karena kami juga terlibat dan sama terpengaruh dengan bencana ini’. Dalam pengelolaannya SPJ menciptakan moda solidaritas berjejaring. Ia tidak berdiri atas satu lembaga atau institusi yang bertanggung jawab dan mengatur jalannya dapur, namun rangkaian kekuatan-kekuatan kecil yang diiinisiasi atas kesadaran tiap elemen warga terlibat, yang tersebar dan saling bergandeng.
Satu hal yang menjadi catatan akan keberadaan SPJ adalah bagaimana rantai ketergantungan dengan pemerintah dan industri seolah terputus, berganti dengan rantai solidaritas saling bantu, antar petani dan rakyat. Paguyuban Petani Lahan Pantai (PPLP) di Kulon Progo dilibatkan langsung dalam penyediaan sayur. Setiap minggunya tiap anggota PPLP membagi sebagian hasil taninya untuk diolah tiap dapur umum. Tidak tanggung-tanggung, satu truk penuh berisi beragam sayuran dibagi tiap minggunya.
Tidak hanya itu saja, rantai ketergantungan bahan pangan yang biasanya dimonopoli oleh pemerintah dan industri, oleh rakyat coba diambil alih, diganti menjadi rantai solidaritas antar warga. Insiatif penyediaan bahan pangan langsung oleh warga salah satunya dilakukan oleh kolektif Kebunku. Mengembalikan kedaulatan pangan ke tangan rakyat merupakan visi besar kawan-kawan yang terlibat disini. Berbekal sebidang lahan terbengkalai, beberapa bibit sayur dan keahlian bertani yang pas-pasan, sekelompok warga yang sama sekali tidak memiliki latar belakang sebagai petani, memberanikan diri untuk membuat kebun sayur organik. Hasil sayurnya tidak mereka jual demi keuntungan, melainkan mereka bagikan ke beberapa dapur umum yang masih membutuhkan, sisanya mereka jual dengan harga murah untuk biaya operasional keberlanjutan kebun.
Seiring dengan semakin longgarnya peraturan PSBB, makin banyak pula warga yang kembali memiliki daya dalam mencari nafkah dan tidak lagi membutuhkan bantuan pangan langsung dari dapur. Saat ini kotak donasi SPJ sudah ditutup, namun beberapa dapur masih terus berjalan. Mengandalkan pemasukan dari donasi yang mereka galang dan kelola sendiri, dapur-dapur tersebut terus mengobarkan api solidaritas antar rakyat. Salah satunya adalah Dapur Sembungan, yang masih aktif membagikan nasi bungkus setiap empat hari dalam seminggu bagi tukang becak, pekerja informal dan buruh serabutan di daerah sekitaran Bantul dan sekitarnya. Sementara ada juga dapur umum Bakzoos yang setiap hari memasak dan mengkhususkan pembagian pangannya bagi buruh gendong di Pasar Beringharjo. Selain kedua dapur tersebut, beberapa dapur umum yang tersebar di kota-kota di Indonesia, seperti Bandung dan Surabaya juga masih terus mengepul. Kesadaran untuk saling bantu adalah satu hal, namun kesadaran untuk terus berdaya dengan semangat solidaritas bagi mereka yang selalu kalah, terlepas dari ada tidaknya bencana, adalah hal lain yang juga patut diapresiasi.
Kegagalan Negara dan Bara Solidaritas
Dua tahun sebelum gonjang-ganjing pandemi terjadi, tepatnya pada tahun 2018, presiden Joko Widodo telah menandatangi Undang-undang No. 6 tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan. Undang-undang ini disusun dengan tujuan melindungi warga Indonesia dari situasi terjadinya pandemi, dimana meluasnya penyakit menular dan kelaparan jadi ancaman terbesar. Situasi seperti sekarang, atau lebih tepatnya delapan bulan yang lalu, saat kasus pertama menyeruak. Sementara banyak negara sudah memberlakukan karantina ketat di wilayahnya, pada 31 Maret 2020 alih-alih memberlakukan UU Kekarantinaan Kesehatan pemerintah justru mengumumkan pemberlakuan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Kebijakan Karantina Wilayah membatasi seluruh anggota masyarakat di suatu wilayah, mereka yang dikarantina tidak boleh keluar masuk wilayah karantina, wilayah karantina dijaga pejabat karantina kesehatan dan polisi, kebutuhan hidup dasar orang hingga hewan ternak yang berada di wilayah karantina menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, melibatkan pemerintah daerah dan pihak yang terkait.
Sementara pembatasan kegiatan wilayah karantina dalam PSBB hanya berupa peliburan sekolah dan tempat kerja dan pembatasan kegiatan keagamaan dan di tempat-tempat umum, penjagaannya tidak spesifik, pemenuhan kebutuhan selama pembatasan diberlakukan tidak diatur, berkoordinasi dan bekerja sama dengan berbagai pihak terkait (tidak spesifik). Pada kenyataannya kebijakan PSBB tidak mengurangi laju orang keluar Jakarta. Data bahkan menunjukkan pada bulan Maret, dua minggu setelah gerakan ‘di rumah aja’ sedang gencarnya dikampanyekan pemerintah, angka laju dari Jakarta ke Yogyakarta meningkat hingga 39%, mengakibatkan meningkatnya jumlah kasus Covid-19 di wilayah tersebut pada akhir Maret 2020, dan ini baru satu contoh saja, Solo dan Surabaya pun mengalami hal serupa. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan karantina wilayah yang konsisten, lebih dibutuhkan ketimbang pembatasan sosial yang penerapannya sendiri diwarnai inkonsistensi pejabatnya sendiri. Namun mungkin saja, mengeluarkan dana untuk memenuhi kebutuhan dasar warganya sendiri selama karantina wilayah adalah hal yang tidak menguntungkan bagi ekonomi negara. Pada akhirnya kesehatan dan keselamatan jiwa warga kalah oleh hitung-hitungan untung rugi kebijakan.
Tidak hanya menyoal kebijakan yang dipilih dan abainya pemerintah dalam kewajiban menjamin kebutuhan dasar warga, kegagalan pemerintah dalam penanganan Covid-19, menurut epidemiolog UGM Bayu Satria, juga dilihat lewat kegagalan dalam menyampaikan pesan pencegahan Covid-19. Salah satunya lewat kurangnya informasi yang diberikan mengenai Covid, pencegahannya, hingga angka pasti penyebarannya. Selain itu inkonsistensi yang diperlihatkan lewat kebijakan dan penerapan yang tidak tegas, juga bagaimana para pejabat sendiri tidak mematuhi protokol kesehatan yang berlaku, juga merupakan satu indikator penyampaian pesan yang gagal. Hal ini menimbulkan kebingungan di masyarakat. Bagi mereka yang cukup melek dan memiliki akses informasi yang mumpuni tentu mampu menilai mana yang terbaik yang seharusnya dilakukan. Sementara bagi mereka yang menjadikan pemerintah sebagai patokan yang benar, tentu tidak ragu untuka mengikuti.
Selain itu, kegagalan pemerintah pusat dalam meningkatkan testing, isolasi dan contact tracing. Bahkan sampai hari ini, banyak pihak profesional yang masih meragukan jumlah testing yang dilakukan pemerintah, karena angka yang tidak sesuai standar testing. Ketiga, ketidakberhasilan pemerintah pusat dalam memantau dan membantu pemerintah daerah dalam menangani situasi pandemi di wilayahnya. Dari segi pantauan, ketidaksinkronan data antara pemerintah Pusat dan Propinsi (seperti yang terjadi di Propinsi Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta dan DIY), merupakan salah satu contohnya.
Tidak berhenti pada bab penanganan saja, masa pandemi tampaknya juga dimanfaatkan pemerintah untuk menggolkan kebijakan-kebijakan yang sangat tidak pro-rakyat dan hanya memberi platform lebih besar bagi kuasa oligark. Beberapa diantaranya RUU Mineral dan Batubara, RUU Mahkamah Konstitusi dan yang terbaru RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law. Sementata RUU Peraturan Kekerasan Seksual sampai detik ini tak kunjung disahkan, dengan alasan ‘terlalu rumit’ dan ‘waktu yang mepet’, sementara data menunjukkan kasus kekerasan seksual pada tahun 2020 ini semakin meningkat.
Fakta menunjukkan bagaimana selama masa pandemi pemerintah sama sekali tidak berpihak pada rakyat. Di tengah sengkarut ancaman virus Covid-19, tenaga kesehatan yang harus menggadaikan nyawa karena kurangnya fasilitas dan tenaga, warga yang harus berjuang untuk bertahan hidup karena tidak tersedianya pangan, belum lagi mereka yang masih harus berupaya memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti listrik dan bensin yang justru meningkat tarifnya selama pandemi, jangankan kewajiban pemenuhan kebutuhan dasar, kebutuhan rakyat atas akses informasi dan jaminan keamanan sama sekali tidak dipenuhi. Kebijakan yang berpihak pada oligarki masih diutamakan, kekerasan aparat masih terjadi, bahkan meningkat, dan nyawa satu persatu terus tumbang karena lumpuhnya penanganan pandemi.
Saat pemerintah tidak lagi bisa diandalkan, kita hanya bisa bergantung pada satu sama lain. Semangat saling bantu dan berbagi harus terus jadi bara untuk saling berpegang dan menyala. Kita harus terus menumbuhkan kesadaran bahwa kita sama-sama terlibat, kita sama-sama jadi korban, kita sama-sama jatuh, untuk itu, adalah tanggung jawab kita bersama untuk saling kait dan menguatkan, bangun dan berjalan maju. Solidaritas merupakan satu-satunya jalan untuk kita dapat bertahan, tidak hanya dalam menghadapi pandemi, tapi juga sebagai jawaban kita untuk terus berjalan dalam meruntuhkan oligarki berwujud negara.
***
Artikel ini merupakan narasi dalam film dokumenter besutan WALHI Yogyakarta berjudul, “Satu tahun Pandemi; GELEGAK SOLIDARITAS DAN SENJAKALA NEGARA,” yang tayang dalam dua episode di kanal YouTube Walhi Yogyakarta. Lihat: Satu tahun Pandemi; GELEGAK SOLIDARITAS DAN SENJAKALA NEGARA (Eps 1) – YouTube & Satu tahun Pandemi; GELEGAK SOLIDARITAS DAN SENJAKALA NEGARA (Eps 2) – YouTube.
W U & Ki